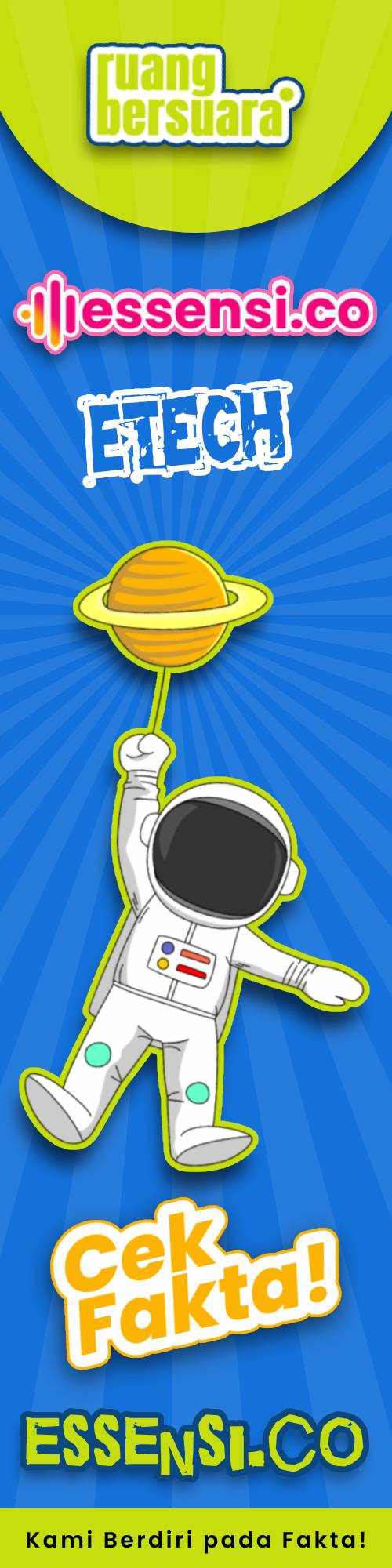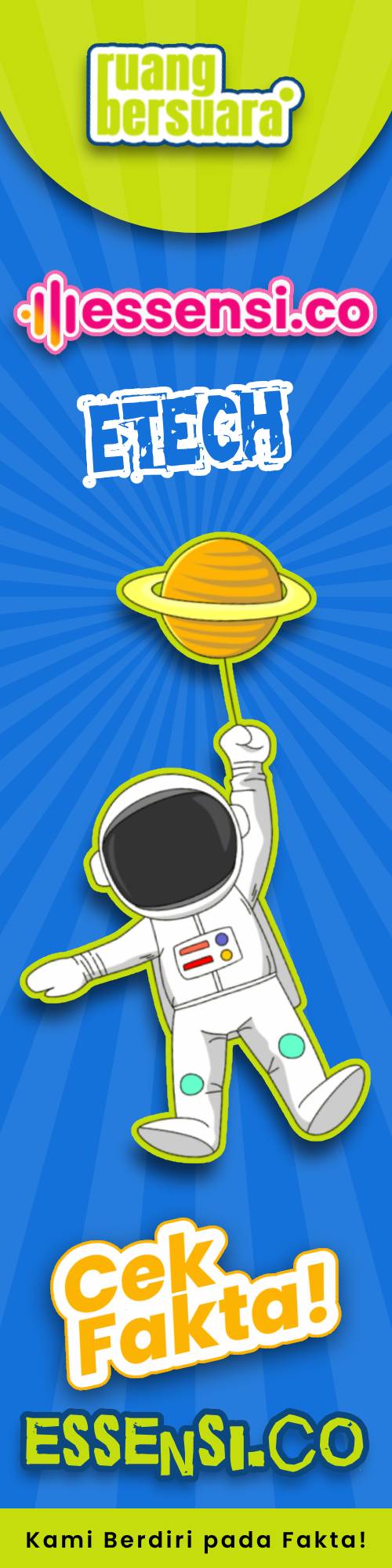Ketika Marhaen Menjadi Penonton di Negeri Sendiri
RUANG BERSUARA – Dalam pusaran zaman yang terus bergerak, bangsa ini dihadapkan pada pertanyaan mendasar: siapa yang sebetulnya menjadi subjek pembangunan? Rakyat atau modal? Marhaen atau elit?
Sejak awal kemerdekaan, Bung Karno meletakkan dasar ideologi bangsa yang berpihak kepada kaum kecil—rakyat yang bekerja dengan alat produksi sendiri, bukan kaum kapital yang menggenggam segalanya. Dari situlah lahir istilah Marhaenisme, sebuah pandangan hidup yang meyakini bahwa kekuatan bangsa ini bersumber dari kerja keras rakyat kecil yang kerap dilupakan.
Bung Karno tidak menemukan Marhaen di buku teori Eropa, melainkan di tanah sendiri. Ia menulis dalam Penyambung Lidah Rakyat:
“Saya tidak hendak membikin rakyat Indonesia menjadi borjuis. Saya hendak membuat rakyat Indonesia menjadi Marhaen yang sadar akan hak dan kewajibannya, yang menguasai alat-alat produksi dan yang hidup dalam masyarakat yang adil dan makmur.”
Marhaen bukanlah sosok pasif. Ia bukan hanya petani yang memegang cangkul atau nelayan yang mendayung perahu kecil. Marhaen adalah lambang rakyat pekerja yang bermartabat. Namun hari ini, wajah Marhaen telah berubah—menjadi buruh pabrik dengan sistem kontrak tanpa kepastian kerja, pengemudi ojek daring yang menggantungkan hidup pada algoritma aplikasi, hingga pedagang kecil yang digusur atas nama proyek strategis.
Ironisnya, dalam negeri yang katanya merdeka dan demokratis ini, Marhaen justru kembali menjadi penonton. Bukan pemain. Pembangunan banyak dijalankan dengan bahasa pertumbuhan ekonomi dan investasi, namun sering kali mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
Kita bisa melihat ini dalam bentuk nyata: penggusuran lahan petani demi kawasan industri, konversi sawah menjadi beton, perampasan ruang hidup masyarakat adat, serta harga kebutuhan pokok yang terus melonjak tanpa perlindungan yang memadai. Marhaen dipaksa bertahan dalam sistem yang tidak lagi berpihak.
Dalam tulisan “Di Bawah Bendera Revolusi”,Bung Karno memperingatkan:
“Revolusi Indonesia adalah revolusi sosial. Ia hendak membebaskan manusia Indonesia dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan.”
Namun apa daya, revolusi itu kini seakan tinggal slogan. Banyak kebijakan lebih ramah pada korporasi ketimbang kepada warga biasa. Bahkan politik elektoral pun jarang mengangkat isu penderitaan rakyat secara serius, karena terlalu sibuk dengan pencitraan dan perebutan kuasa.
Padahal, jika kita benar-benar ingin membangun bangsa yang kuat dan berdaulat, maka tidak ada jalan lain selain kembali kepada kekuatan rakyat. Marhaenisme bukan anti-investasi, tetapi menuntut keadilan. Ia tidak menolak modernisasi, tetapi menolak eksploitasi.
Dalam Buku “Amanat Penderitaan Rakyat”, Bung Karno berujar:
“Selama di negeri ini masih ada kemiskinan, masih ada kelaparan, dan masih ada penindasan, maka revolusi belum selesai!”
Itulah yang seharusnya menjadi cermin bagi setiap pemimpin hari ini. Bahwa tugas kenegaraan bukan hanya menyejahterakan statistik, melainkan menyejahterakan manusia. Pembangunan bukan hanya tentang gedung dan jalan tol, tapi tentang ruang hidup yang adil bagi semua.
Sudah waktunya kita tidak lagi membiarkan Marhaen menjadi penonton di tanahnya sendiri. Ia harus diajak bicara, diberi ruang untuk tumbuh, dan dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan. Kekuatan sejati bangsa ini bukan pada modal asing, bukan pada elite-elite partai, tapi pada rakyat yang bekerja jujur, mencangkul tanah, menjahit pakaian, mengangkut barang, dan menjaga api dapur tetap menyala.
Marhaenisme bukan nostalgia masa lalu. Ia adalah peta jalan menuju masa depan yang adil dan berdaulat. Yang tinggal, apakah kita masih punya keberanian untuk berpihak?