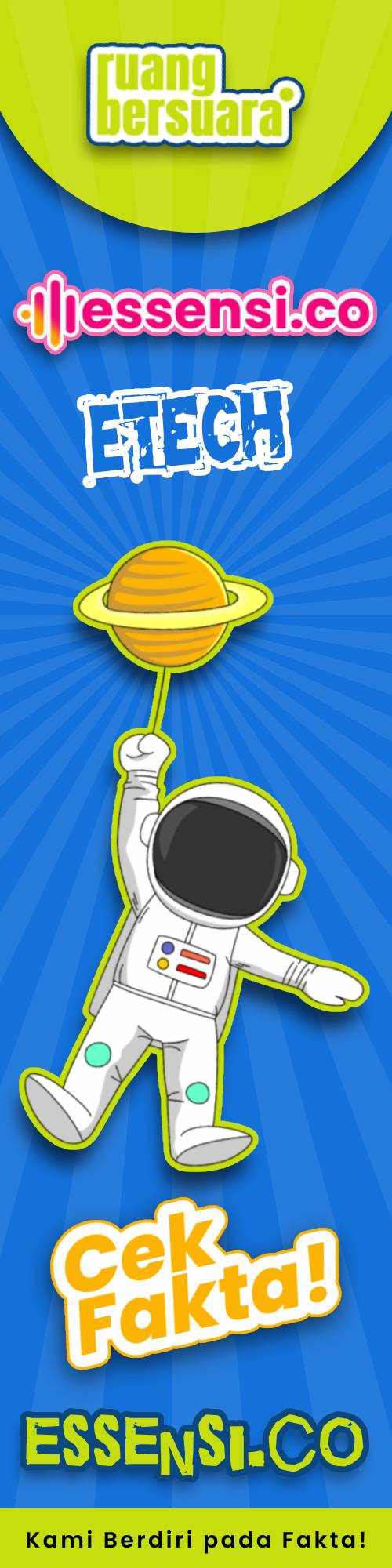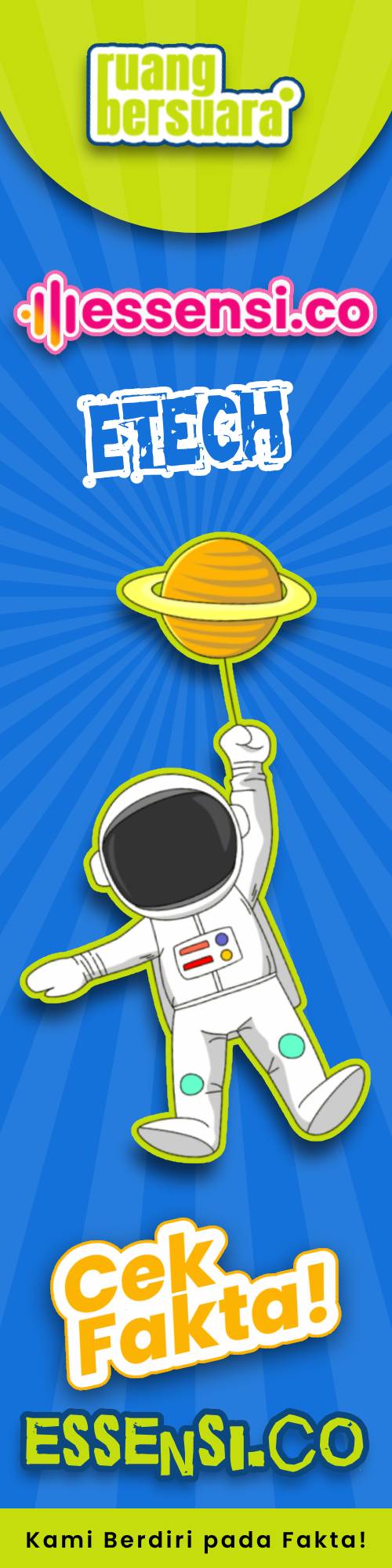Suara Peluru di Semanggi: Luka Lama yang Belum Sembuh
Jakarta, Mei 1998 – Desember 1999. Dalam rentang waktu singkat, dua tragedi besar yang mengguncang Jakarta mengukir luka dalam sejarah bangsa. Dua titik waktu yang kelam—Tragedi Semanggi I dan II—menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan demokrasi berbalut darah dan air mata.
Hingga kini, lebih dari dua dekade kemudian, luka Semanggi belum pernah benar-benar sembuh, dan keadilan yang dijanjikan masih menggantung di langit demokrasi yang kabur.
Latar Belakang: Reformasi dan Gejolak Transisi Kekuasaan
Tragedi Semanggi terjadi di tengah pergolakan reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, bangsa ini memasuki masa transisi penuh ketegangan.
Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan nyata dan penghapusan sisa-sisa otoritarianisme, termasuk peran militer dalam politik sipil. Namun, transisi yang diharapkan damai justru disambut oleh represi keras aparat keamanan.
Semanggi I: November 1998
Pada tanggal 13 November 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menolak pengesahan Undang-Undang Keadaan Darurat, yang dianggap membuka jalan bagi militer kembali mengontrol sipil. Mereka berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi, salah satu titik strategis di jantung ibu kota.
Aparat TNI dan Polri membubarkan demonstrasi dengan kekuatan brutal. Gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam digunakan. Hasilnya:
-
17 orang tewas, sebagian besar warga sipil dan mahasiswa
-
Puluhan lainnya luka-luka
-
Negara menyebutnya “kerusuhan”, tapi keluarga korban menyebutnya “pembantaian”
Semanggi II: September 1999
Belum genap setahun, Tragedi Semanggi II kembali mengguncang. Kali ini, demonstrasi menentang pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan peran militer dalam DPR/MPR. Pada 24 September 1999, mahasiswa yang melakukan aksi damai kembali disambut peluru. Data Komnas HAM menyebutkan:
-
12 korban jiwa, termasuk mahasiswa Universitas Indonesia, dan
-
Banyak korban luka akibat tembakan dan pukulan aparat
Hilangnya Jejak Keadilan
Meski dua tragedi ini jelas menyisakan korban dan saksi, hingga kini belum ada satu pun pelaku diadili di pengadilan HAM. Pemerintah dan DPR berkali-kali menyebut kasus ini “bukan pelanggaran HAM berat”. Sementara Komnas HAM berulang kali merekomendasikan penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.
Keluarga korban tak pernah lelah menuntut keadilan. Setiap Kamis, mereka berdiri di depan Istana Negara dalam aksi yang dikenal sebagai “Kamisan”, membawa foto anak-anak mereka yang tewas dengan satu pesan sederhana: “Kami tidak lupa.”
Kesaksian yang Tak Terhapus Waktu
Heryanto (70), ayah dari salah satu korban, mengenang detik-detik saat putranya tak pernah pulang.“Dia hanya ingin negara ini lebih adil, tapi malah diberi peluru,” katanya lirih.
Refleksi: Antara Ingatan dan Harapan
Tragedi Semanggi adalah simbol dari ketimpangan antara negara dan warganya. Ketika mahasiswa bicara tentang keadilan, negara menjawab dengan kekerasan. Ketika rakyat menuntut reformasi, yang datang justru represi.
Kini, generasi muda ditantang untuk tidak melupakan sejarah ini. Bukan untuk menebar luka lama, tapi agar bangsa ini tidak jatuh ke lubang yang sama.
“Melupakan Semanggi berarti membuka jalan bagi kekerasan negara kembali berulang.”